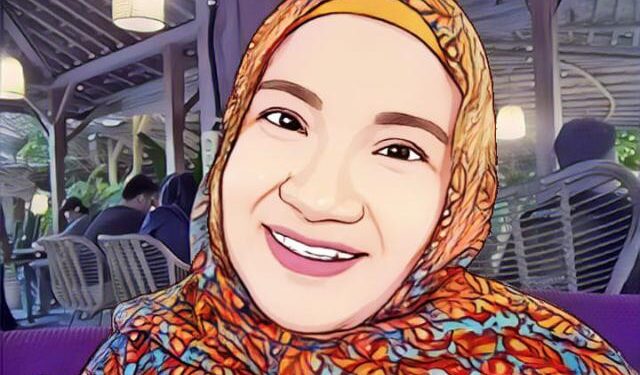Penulis: Eva Riana Rusdi – Kandidat Doktor Imu Sejarah Universitas Indonesia
Indonesia patut berbangga dengan pencapaian keterwakilan perempuan di DPR yang mencapai 20,8% atau 120 orang dari 575 anggota pada periode 2019-2024 dan pada periode 2024-2029 naik menjadi 127 orang dari 580 anggota. Persentase keterwakilan perempuan di DPR RI yang tertinggi dalam sejarah parlemen Indonesia. Menariknya, pada dua periode ini pula Ketua DPR RI terpilih adalah seorang Perempuan, yaitu Puan Maharani (PDI Perjuangan). Namun, pencapaian ini menyisakan paradoks yang menggelitik: mengapa dengan keterwakilan yang semakin tinggi, isu-isu perempuan justru masih terpinggirkan dalam agenda legislasi nasional?
Data Badan Legislasi DPR menunjukkan fakta yang mengejutkan. Dalam lima tahun terakhir, dari 256 RUU yang dibahas, hanya sekitar 8 persen yang secara eksplisit responsif terhadap kebutuhan perempuan. Bahkan produk hukum yang lahir seperti UU Cipta Kerja justru dinilai merugikan pekerja perempuan karena mengabaikan aspek perlindungan khusus bagi ibu hamil dan menyusui.
Ironi ini semakin kentara ketika melihat isu-isu krusial perempuan yang mangkrak bertahun-tahun. RUU Kesetaraan Gender tertunda sejak 2012, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga masih dalam tahap pembahasan yang alot, dan berbagai usulan terkait kesehatan reproduksi seringkali kandas di tengah jalan karena dianggap “sensitif”.
Mengapa hal ini terjadi? Pertama, masalah kapasitas. Meski secara kuantitas meningkat, banyak anggota DPR perempuan yang masih belum memiliki pemahaman mendalam tentang perspektif gender dalam penyusunan kebijakan. Kedua, prioritas politik yang bias. Sistem politik kita masih menempatkan isu ekonomi dan politik sebagai “isu besar”, sementara isu perempuan dianggap “isu pinggiran”. Ketiga, tekanan struktur patriarki yang mengakar dalam budaya politik Indonesia, di mana suara perempuan sering dianggap kurang legitimate dalam membahas kebijakan publik.
Perjuangan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi contoh nyata betapa berlikunya jalan isu perempuan di parlemen. RUU ini membutuhkan waktu hampir satu dekade, dari 2012 hingga akhirnya disahkan pada 2022. Proses yang panjang ini bukan karena kompleksitas teknis, melainkan resistensi politik dan sosial yang luar biasa besar. Padahal, data Komnas Perempuan menunjukkan angka kekerasan seksual yang terus meningkat setiap tahunnya.
Kesuksesan pengesahan UU TPKS sebenarnya memberikan pelajaran berharga. Kunci utamanya adalah solidaritas lintas partai di antara anggota perempuan, dukungan masif dari organisasi masyarakat sipil, dan tekanan publik yang konsisten. Ini membuktikan bahwa ketika ada komitmen politik yang kuat, isu perempuan bisa menjadi prioritas legislasi.
Untuk mengubah situasi ini, diperlukan strategi komprehensif. Pertama, penguatan kapasitas anggota DPR perempuan melalui pendidikan politik yang berbasis gender. Kedua, pembentukan aliansi strategis lintas fraksi untuk mengawal isu-isu perempuan. Ketiga, integrasi perspektif gender dalam setiap tahapan penyusunan undang-undang, bukan hanya sebagai pertimbangan tambahan.
Yang terpenting, perlu ada perubahan paradigma dalam melihat isu perempuan. Ini bukan sekadar “isu khusus” yang hanya relevan bagi setengah populasi, melainkan isu keadilan yang menyangkut pembangunan bangsa secara keseluruhan. Ketika perempuan terlindungi dan mendapat kesempatan yang sama, seluruh masyarakat akan merasakan manfaatnya.
Keterwakilan numerik tanpa representasi substansial hanyalah angka kosong. Saatnya mengubah paradoks ini menjadi momentum transformasi nyata bagi kemajuan perempuan Indonesia.